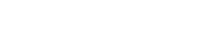LAMPUNG DALAM POTRET LITERASI: ANTARA CAPAIAN DAN KETERTINGGALAN

Dr. Eka Sofia Agustina, M.Pd.-Ist-
Awal mula sistem tulis atau aksara muncul sekitar 3.200 SM di Mesoppotamia (Sumeria) lalu diikuti wilayah Mesir dengan tujuan awal untuk pencatatan dagang, hukum, pendidikan dan pewarisan pengetahuan, serta keagamaan. Dimulai dengann bentuk aksara piktograf, ideogram, abjad fonetik. Hal Ini berdampak pada berkembangnya peradaban, ilmu, dan dokumentasi sejarah. Aksara adalah sistem lambang visual yang mewakili bunyi, suku kata, atau kata dalam bahasa manusia. "Aksara"secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu akṣara yang bisa berarti 'huruf', 'bunyi' atau 'vokal'. Aksara juga dapat berarti "tak termusnahkan", yang berasal dari kata a+kṣara. Awalan a- berarti 'tidak', sedangkan kṣara berarti 'termusnahkan'. Aksara dianggap sebagai sesuatu yang kekal karena berperan dalam mendokumentasikan dan mengabadikan peristiwa komunikasi dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, kesuraman dan kejayaan masa lalu dapat dijamah kembali melalui bukti-bukti literal. Secara terminologi, istilah lain untuk menyebut aksara adalah huruf atau abjad (bahasa Arab), yang dimengerti sebagai lambang bunyi bahasa (fonem). Sedangkan bunyi itu sendiri adalah lambang pengertian yang menurut catatan sejarah secara garis besar yakni Piktogram; Ideogram; Abjad suku kata; dan Abjad fonetik lalu dibagi kembali menjadi bebrapa jenis dalam kelompok besar tersebut.
Aksara menjadi bagian dari bahasa manusia sebagai perkembangan lanjutan dari sistem komunikasi lisan, yang berfungsi untuk merekam, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara lebih permanen. Proses ini terjadi seiring dengan pertumbuhan peradaban manusia, khususnya saat manusia mulai hidup menetap, bertani, berdagang, dan membentuk sistem pemerintahan. Dengan demikian, manusia menciptakan sistem tulisan atau aksara sebagai representasi visual dari bahasa lisan.
Sintesis dari hal tersebut adalah aksara penting bagi bahasa dan peradaban karena digunakan sebagai perservasi budaya (Kitab kuno, cerita rakyat, hukum adat, semua bisa diwariskan); Ilmu pengetahuan (tulisan memungkinkan kolaborasi dan pengembangan gagasan) dan identitas kolektif: Aksara menjadi simbol budaya (contoh: aksara Lampung, Ulu, Arab Pegon/Jawi, Jawa, Sunda, Bali, Sasak, Lontara, Lontara Modifikasi, Kutai, Sumba, dan Batak. Pada unsur aksara menjadi simbol budaya karena bahasa daerahnya berkembang secara lisan dari masa ke masa, penuh kosakata dan struktur bahasa yang khas.
Secara teoretis, jenis aksara terdiri atas pitograf, ideograf, alfabet, abjad, abugida, dan silsilah. Indonesia secara nasional dominan menggunakan aksara Latin sebagai sistem tulisan resminya, terutama untuk bahasa Indonesia dan sebagian besar bahasa daerah yang sudah dialihaksarakan. Namun, kalau dilihat secara kultural dan historis, Indonesia memiliki banyak aksara tradisional yang masuk ke dalam kategori aksara abugida dan abjad, bergantung daerahnya yang masih hidup dalam berbagai komunitas dan upaya pelestarian, seperti aksara Lampung.
Definisi operasional kata "Aksara" dalam konteks ini merujuk pada "literasi", bukan hanya kemampuan mengenal huruf atau tulisan, tetapi juga kemampuan memahami, menggunakan, dan merefleksikan informasi tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Istilah "literacy" dalam bahasa Inggris mencakup makna yang lebih luas dari sekadar mengenal huruf termasuk kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan literasi media. Selain itu, masalah literasi juga erat kaitannya dengan ketimpangan sosial. Data UNESCO menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak di daerah terpencil menjadi korban paling rentan. Mereka menghadapi siklus kemiskinan yang sulit diputus karena akses pendidikan yang minim. Peringatan Hari Aksara Internasional mengingatkan kita bahwa literasi adalah jembatan untuk keluar dari kemiskinan. Ketika anak-anak diberi kesempatan belajar membaca dan menulis, mereka sedang diberi kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Namun, jika kesempatan itu tak diberikan, mereka terjebak dalam lingkaran ketertinggalan.
Di tengah perkembangan teknologi digital, literasi juga mengalami perluasan makna. Sekarang, kita tidak hanya dituntut bisa membaca buku, tetapi juga memahami dan menilai informasi yang tersebar di internet, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, kemajuan teknologi juga menimbulkan paradoks. Di satu sisi, teknologi membuka akses informasi yang luas; di sisi lain, mereka yang tidak melek digital justru semakin terpinggirkan. Hari Aksara Internasional menjadi panggilan bagi kita semua untuk tidak hanya memerangi buta aksara konvensional, tetapi juga buta huruf digital.
Bagaimana potret literasi di Provinsi Lampung? Penulis mendapatkan data pertahun 2023. Berdasarkan data statistik dan indeks literasi di Lampung dengan 5 pengelompokkan yang terdiri atas (1) Buta Aksara di Kalangan Lansia; Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM); Literasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan; Tingkat Melek Huruf di Beberapa Kabupaten; dan Minat Membaca Masyarakat (Tingkat Kegemaran Membaca). Untuk Buta Aksara di Kalangan Lansia tahun 2023 berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, sekitar 15 orang lansia dari setiap 100 orang tidak bisa membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya, setara dengan 14,72 % dari populasi lansia di Lampung pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan perbaikan, meski masih signifikan, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2022: 15,71 % dan 2021: 16,61 %. Untuk kategori Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2022: IPLM Lampung sebesar 59,99, berada di bawah rata-rata nasional (~64,48); 2023: Nilainya menurun menjadi 55,25, masih termasuk kategori "Sedang", dan berdiri di bawah rata-rata nasional (~69,42). IPLM mencakup indikator seperti pemerataan layanan perpustakaan, kualitas koleksi, partisipasi masyarakat, dan sejumlah aspek lainnya.
Kategori literasi berdasarkan Tingkat Pendidikan menurut Renstra BPMP Lampung (2020–2024 revisi 2023), capaian literasi berdasarkan jenjang pendidikan: SD/SLB: Skor rata-rata 57,89 (kategori sedang – menempati peringkat menengah bawah nasional); SMP: Literasi di Lampung rata-rata 60,06, peningkatan signifikan dari sebelumnya 47,88, berada di peringkat menengah atas nasional. Dua kota terbaik adalah Bandar Lampung dan Metro; SMA: Rata-rata 52,31, mengalami penurunan dari 55,11 peringkat menengah nasional. Hanya Kota Metro yang berada di kategori "Baik", sementara dua wilayah yaitu Lampung Utara dan Pesisir Barat masih di kategori "Kurang; SMK: Literasi rata-rata 41,4, turun dari 48,17 masuk tingkat “sedang”. Banyak kabupaten/kota (7 dari 15) berada di kategori "Kurang". Selanjutnya, Tingkat Melek Huruf di Beberapa Kabupaten dalam IDN Times (mengacu data BPS 2024), lima kabupaten/kota dengan angka melek huruf terendah (usia 15+) di Lampung: Lampung Tengah: 96,81 %; Tanggamus: 96,78 %; Lampung Selatan: 96,53 %. Meskipun angka ini terbilang tinggi, namun jika di bawah 97%, menunjukkan masih ada segmen masyarakat yang belum sepenuhnya melek huruf. Terakhir, kategori Minat Membaca Masyarakat (Tingkat Kegemaran Membaca), menurut dataset dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung Indeks Minat Membaca (TGM) 2023: Lampung secara umum mencapai 66,38. Lalu tahun 2024: Kota Bandar Lampung (78,71) dan Metro (78,43) berada di atas rata-rata provinsi, yang kini menjadi 67,67.
Berdasarkan data Laporan Akhir IPLM 2024 Skor rata-rata Provinsi Lampung: 64,81 (kategori: Sedang). Wilayah Kota Metro 96,96; Kabupaten Tulang Bawang 64,11; Kota Bandar Lampung 66,28; Kabupaten Lampung Barat 63,08; Kabupaten Mesuji 56,30; Kabupaten Pesawaran 57,75; Kabupaten Pesisir Barat 52,89; Kabupaten Pringsewu 51,81; Kabupaten Tanggamus 49,04; Kabupaten Lampung Selatan 44,56; Kabupaten Lampung Tengah 43,61; dan Kabupaten Lampung Timur 43,04. Penulis belum mendapatkan data ILPM Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan. Jadi, Daerah dengan pencapaian tertinggi: Kota Metro dengan angka 96,96 dan daerah dengan pencapaian terendah yakni Kabupaten Lampung Timur dengan angka 43,04
Tentu temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antar daerah dalam hal pembangunan literasi. Daerah seperti Lampung Timur perlu perhatian khusus, sementara Metro sangat menjanjikan, perlu strategi untuk duplikasi keberhasilan tersebut. Analisis yang bisa saya sajikan dari capaian itu adalah Kesenjangan Antardaerah dengan IPLM Kota Metro sangat tinggi (96,96), mencerminkan akses literasi yang sangat baik. Namun, skor rendah di banyak kabupaten seperti Lampung Timur (43,04) dan Lampung Tengah (43,61) menunjukkan disparitas akses dan kualitas literasi. Potensi perbaikan melalui bisa melalui kolaborasi. Data ini menjadi dasar penting untuk menyusun intervensi berbasis kebutuhan: misalnya peningkatan fasilitas perpustakaan, pelatihan tenaga literasi, dan kampanye baca lokal di daerah dengan skor rendah. Model Kota Metro, dengan skor tinggi seperti Metro dan Bandar Lampung bisa dijadikan best practice. Analisis terhadap faktor kunci keberhasilan mereka seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat yang dapat membantu merancang program peningkatan literasi di wilayah lain.
Rekomendasi strategi peningkatan literasi harus disesuaikan dengan karakteristik lokal: demografi, infrastruktur, ekonomi, sosial-budaya, dan tingkat partisipasi masyarakat. Berdasarkan data IPLM kabupaten/kota di Lampung yang sangat beragam (dari skor di bawah 45 hingga di atas 90), berikut adalah strategi peningkatan literasi yang kontekstual untuk Provinsi Lampung. Daerah Skor Tinggi (IPLM > 65) Kota Metro dan Bandar Lampung memiliki karakteristik: Kota urban; Infrastruktur pendidikan relatif lengkap; Akses internet baik; Kesadaran literasi masyarakat tinggi. Strategi Rekomendasi yang bisa diberikan antara lain melalui (1)digitalisasi literasi: dorong literasi digital, media, dan informasi. Fokus pada penguatan literasi kritis (anti-hoaks, keamanan siber, berpikir analitis); (2) literasi tematik: literasi finansial, literasi lingkungan, literasi Kesehatan; (3) perluas peran komunitas baca dan perpustakaan sebagai ruang diskusi, inovasi, dan literasi aktif; dan (4) duplikasi model sukses ke daerah lain: dokumentasikan program unggulan untuk ditransfer ke daerah lain.