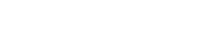LAMPUNG DALAM POTRET LITERASI: ANTARA CAPAIAN DAN KETERTINGGALAN

Dr. Eka Sofia Agustina, M.Pd.-Ist-
Oleh: Dr. Eka Sofia Agustina, M.Pd.
(Akademisi FKIP Unila dan Dewan Pembina Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia Wilayah Provinsi Lampung)
Aksara adalah bentuk konkret dari bahasa yang memungkinkan manusia “berbicara melintasi waktu”.
Tulisan ini saya awali dengan menyegarkan kembali ingatan kita bersama mengapa UNESCO menetapkan tanggal 8 September sebagai International Literacy Day atau Hari Aksara Internasional (HAI). Semangat peringatan tentang momentum ini adalah untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya literasi sebagai satu isu hak asasi manusia pada lingkup pendidikan dan kesejahteraan. Dalam catatan sejarahnya, diawali dengan penyampaian bahwa umat manusia sejak 8000 tahun sebelum masehi sudah mengenal akksara sebagai alat dalam berkomunikasi. Namun, sampai tahun 1965 masih terdapat 350 juta orang yang ada dipenjuru dunia masih buta huruf, termasuk Indonesia. Permasalahan global tersebut tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena literasi menjadi salah satu factor terpenting yang mendorong kemakmuran masyarakat di suatu negara. Akhirnya, pada 8 September 1965 diselenggarakanlah konferensi dunia oleh UNESCO yang bertema “World Conference of Ministers of Education on the Eradication of Illiteracy” di Teheran, Iran.
Dalam konferensi tersebut, Pemerintah Republik Iran mengusulkan sebuah ide supaya UNESCO untuk memberikan hadiah apresiasi kepada individu-individu yang berjasa dalam perjuangan melawan buta huruf. Permohonon tersebut secara resmi dikabulkan UNESCO pada tahun 1966 dan sekaligus mendeklarasikan tanggal 8 September sebagai Hari Aksara Internasional. Selanjutnya, peringatan Hari Aksara Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1967 tanggal 8 September di seluruh dunia untuk mengingatkan para pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat tentang pentingnya literasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih melek huruf, adil, damai, dan berkelanjutan oleh masyarakat global. Selain itu, setiap tahunnya UNESCO juga memberikan reward kepada masyarakat internasional yang memiliki jasa dalam upaya perjuangan melawan buta huruf.
Sekitar tahun 1990, pentingnya peran literasi semakin disorot dunia ketika konferensi dunia “Education for All” yang diadakan di Jomtien, Thailand. Kemudian berlanjut pada tahun 2015, literasi menjadi poin terpenting dalam salah satu tujuan utama Sustainable Development Goals (SDGs) bidang pendidikan. SDGs sendiri adalah sebuah rencana aksi global yang disepakati para pemimpin-pemimpin dunia termasuk Indonesia, yang memiliki tujuan menamatkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan melindungi lingkungan dunia. Bahkan sejak digitalisasi semakin berkembang pesat, pada tahun 2017 fokus Hari Aksara Internasional melebar sampai kepada keterampilan literasi digital.
Momentum setiap tahun, tanggal 8 September menjadi hal reflektif bagi dunia untuk berhenti sejenak dan merenung tentang sesuatu yang sering kita anggap remeh: kemampuan membaca dan menulis. Esensi merayakan Hari Aksara Internasional bukan hanya sebagai simbol pendidikan melainkan sebagai panggilan hati dari ruang kemanusiaan. Secara teoretis, terdapat 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai manusia yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Membaca dan menulis merupakan dua keterampilan yang mungkin bagi banyak dari kita tampak biasa saja tetapi sebenarnya adalah hal itu kunci untuk membuka “dunia”.
Sayangnya, berdasarkan data UNESCO Institute for Statistics pertahun 2025, masih terdapat sekitar 754 juta orang dewasa yang masih buta aksara di seluruh dunia. Angka rata-rata melek huruf global (literacy rate) adalah sekitar 86,3 %, sehingga menyisakan sekitar 13,7 % populasi orang dewasa yang masih buta aksara. Dengan demikian, angka buta aksara di dunia masih tergolong tinggi, dengan ratusan juta orang dewasa yang belum mampu menikmati hak dasar untuk membaca dan menulis. Di balik angka-angka ini, tentu ada wajah-wajah manusia yang terhambat dalam mengakses informasi, pendidikan, dan peluang hidup yang lebih baik. Meski begitu, harapan tetap besar dengan adanya perhatian global melalui inisiatif seperti Target 4.6 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), berbagai upaya terus digalakkan agar setiap individu, di manapun berada, memiliki kesempatan untuk melek huruf dan meraih masa depan yang lebih layak. SDGs sendiri adalah sebuah rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin-pemimpin dunia termasuk Indonesia, yang memiliki tujuan menamatkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan melindungi lingkungan dunia. Bahkan, sejak digitalisasi semakin berkembang pesat, pada tahun 2017 fokus Hari Aksara Internasional melebar sampai kepada keterampilan literasi digital.
Itu adalah potret dunia, Indonesia tentu menjadi bagian di dalamnya dan yang lebih khusus lagi Lampung pula menjadi bagian dari penyumbang data dunia. Bagaimana dengan potret literasi di Provinsi Lampung?
Sebelum menuju kupasan hal tersebut, saya ulas lebih dahulu secara konseptual bahasa dan aksara. Bahasa muncul sebagai hasil dari evolusi biologis, kebutuhan sosial, dan perkembangan simbolik manusia. Ia menjadi "disepakati" karena manusia adalah makhluk sosial yang membentuk makna bersama melalui komunikasi terus-menerus. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat berpikir, pembentuk budaya, dan identitas manusia. Bahasa menjadi disepakati karena Manusia hidup dalam kelompok yang berulang-ulang menggunakan simbol atau bunyi tertentu untuk merujuk pada objek, tindakan, atau ide. Seiring waktu, kelompok tersebut menstandarkan lambang-lambang itu melalui pengulangan, transmisi antar generasi, dan norma sosial. Maka, lahirlah sistem bahasa, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat yang terus berkembang.
Lalu bagaimana asal mula munculnya bahasa? Tentu itu pertanyaan mendasar dan kompleks dalam bidang linguistik, antropologi, dan evolusi manusia yang disepakati oleh manusia. Tidak ada satu jawaban pasti, karena tidak ada bukti tertulis dari masa awal manusia berbicara. Namun, para ilmuwan telah mengembangkan berbagai teori ilmiah dan hipotesis untuk menjelaskan bagaimana bahasa pertama kali muncul dan menjadi sistem komunikasi yang disepakati. Seperti beberapa teori asal usul bahasa yakni Teori Evolusi Biologis (Charles Darwin); Teori Sosial (Bahasa Sebagai Produk Kebutuhan Sosial); Teori Imitasi atau "Bow-wow Theory"; Teori Gesture (Bahasa Tumbuh dari Bahasa Tubuh); dan Teori Monogenesis dan. Polygenesis. Tidak ada catatan pasti tentang "bahasa pertama" di dunia karena bahasa muncul sebelum tulisan. Namun, beberapa bahasa tertua yang tercatat dalam tulisan kuno yakni Sumeria (Irak) – sekitar 3.000 SM; Akkadia, Mesir Kuno, Sansekerta, dan Tamil (yang masih digunakan hingga kini). Tapi tentu, bahasa lisan manusia muncul jauh lebih awal dari itu yang diperkirakan sekitar 50.000–100.000 tahun lalu.
Dengan demikian, bahasa lisan adalah bentuk komunikasi paling awal yang digunakan manusia, bentuk awal mendahului aksara. Ia tumbuh secara alami melalui interaksi sosial dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Namun, bahasa lisan tidak meninggalkan jejak fisik, sehingga sulit untuk menjaga keutuhan informasi dari waktu ke waktu. Baru saat peradaban manusia muncul, kebutuhan akan sistem tulis menjadi sangat dibutuhkan manusia. Awal mula munculnya sistem tulis atau aksara sebagai representasi bahasa lisan manusia terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu, dan menandai salah satu tonggak terpenting dalam sejarah peradaban manusia.