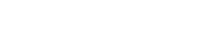Keadilan Buruh, Keadilan Sosial

Radar Lampung Baca Koran--
Masa kolonial memperlihatkan bagaimana buruh menjadi kekuatan politik yang signifikan. Pendirian Perserikatan Komunis di Hindia pada 1920-an banyak melibatkan elemen buruh, dan pemogokan massal menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial.
Pasca kemerdekaan, buruh tetap menjadi aktor penting dalam dinamika politik nasional, terutama melalui organisasi seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia.
Namun, tragedi politik 1965 menjadi titik balik kelam bagi gerakan buruh. Dengan dibubarkannya SOBSI dan pembasmian kekuatan-kekuatan progresif, gerakan buruh di Indonesia lumpuh selama bertahun-tahun di bawah rezim Orde Baru.
Buruh dipaksa tunduk pada serikat pekerja tunggal yang dikendalikan negara, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), dan segala bentuk gerakan independen diberangus secara brutal.
Kebangkitan gerakan buruh baru terjadi menjelang kejatuhan Orde Baru di akhir 1990-an. Reformasi politik membuka ruang bagi kebebasan berserikat, yang kemudian melahirkan banyak serikat buruh independen. Namun, tantangan baru pun muncul dalam bentuk fragmentasi dan lemahnya konsolidasi gerakan.
Sejak era reformasi, gerakan buruh Indonesia mencatat beberapa capaian penting. Salah satu pencapaian monumental adalah pengesahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memberi perlindungan lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Selain itu, buruh berhasil mendorong pengakuan atas hak-hak normatif seperti upah minimum, hak cuti melahirkan, dan perlindungan terhadap diskriminasi.
Namun demikian, gerakan buruh juga menghadapi banyak kegagalan. Salah satu kegagalan terbesar adalah ketidakmampuan untuk mencegah lahirnya kebijakan-kebijakan pro-pasar seperti Omnibus Law.
Dalam kasus ini, meskipun terjadi mobilisasi massa besar-besaran, kekuatan gerakan buruh tidak cukup untuk membendung tekanan politik dan ekonomi dari oligarki bisnis.
Kegagalan ini mencerminkan lemahnya kekuatan lobby politik buruh, ketidakmampuan membangun aliansi strategis dengan gerakan sipil lainnya, serta minimnya kaderisasi politik di dalam tubuh serikat pekerja sendiri.
Salah satu masalah kronis dalam gerakan buruh Indonesia adalah fragmentasi organisasi. Terdapat ratusan serikat buruh di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat perusahaan hingga tingkat nasional, yang sering kali berjalan sendiri-sendiri bahkan saling bersaing.
Fragmentasi ini bukan hanya soal jumlah organisasi, tetapi juga perbedaan orientasi, strategi, dan kepentingan antar serikat. Ada serikat yang fokus pada pendekatan legal-formal, ada pula yang lebih militans, sementara sebagian lainnya pragmatis dengan melakukan kompromi terhadap perusahaan atau pemerintah.
Ketiadaan koordinasi yang solid membuat kekuatan buruh terpecah, melemahkan posisi tawar mereka dalam negosiasi dengan pemerintah maupun pengusaha. Kondisi ini diperparah dengan ego sektoral dan kurangnya visi jangka panjang untuk membangun gerakan buruh sebagai kekuatan politik nasional.
Perubahan ekonomi global memperkenalkan bentuk-bentuk baru hubungan kerja, terutama melalui digitalisasi. Pekerja platform seperti pengemudi ojek online, pekerja lepas digital (freelancer), dan buruh kreatif kini membentuk segmen besar dalam dunia kerja. Mereka bekerja dalam sistem yang sangat fleksibel, namun tanpa perlindungan formal seperti upah minimum, jaminan sosial, atau hak berunding kolektif.
Gerakan buruh tradisional seringkali belum mampu merangkul kelompok pekerja baru ini. Model serikat pekerja konvensional sulit diterapkan pada pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja formal, apalagi dengan sistem kerja berbasis algoritma dan platform digital.