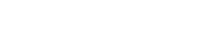Bronze

-ILUSTRASI AATLAS/PIXABAY -
Aku menatap ibuku.
“Berjanjilah pada Ibu,” Ibuku tersenyum, “jangan pernah tinggalkan panjat tebing.”
Setelah itu, tepat sekali setelah saat itu, sebelum aku sempat menjawab perkataan ibuku, sebelum aku sempat membalas senyumannya, sebelum aku sempat melihat mata bronze-nya dengan lebih dalam, tiba-tiba batu pijakan kaki ibuku luruh diikuti dengan batu yang menyangga kedua tangannya. Tubuh ibuku terhempas begitu saja menuruni tebing dengan kecepatan penuh.
“Ibuuuu!” Aku berteriak kencang, meraung histeris.
Dari kejauhan, aku bisa melihat dengan jelas. Saat itu tubuh ibuku meluncur tanpa pengaman ke dasar tebing. Ibuku berkali-kali mencoba meraih permukaan tebing, tetapi pasir yang berjatuhan dalam jumlah yang banyak membuat pegangannya menjadi licin dan ia kembali terjun bebas. Akhirnya, aku mendengar tubuh ibuku berdebum menghantam tanah di bawah sana, diikuti dengan miliaran debu yang terbang ke udara, dan suara tulang-tulang yang remuk akibat dentuman keras.
“Brakkkkk!”
Seketika saat itu juga aku merasa duniaku hancur lebur. Memori tentang segala hal yang baru saja kami lakukan mulai berputar. Padahal, baru saja, baru saja satu jam yang lalu kami tertawa bersama, bercanda ria, memikirkan masa depan. Padahal, baru saja kami menikmati kebersamaan dan kebahagiaan setelah terpukul akan kematian ayahku. Padahal, baru saja kami berdua duduk santai sambil menikmati pemandangan indah, mengobrol santai, dan merasakan semilir angin yang segar. Namun, kini ibuku sudah jatuh dari ketinggian lebih dari tiga ribu kaki itu, berdebum di tanah. Aku tidak tahu sudah mati atau masih hidup. Mengingatnya saja membuat aku semakin meraung histeris.
“Ibu...hiks!”
Saat itu aku menunggu di atas ketinggian selama hampir lima jam, menggantung-gantung tak tentu arah sambil menunggu pertolongan. Beberapa kali aku mencoba membuat kode pertolongan menggunakan api, membuat kode-kode morse, meniupkan peluit, sampai membuat suara-suara ribut untuk meminta pertolongan. Beberapa jam kemudian, sebuah helikopter penyelamat datang, lalu menolongku dan mengevakuasi ibuku dari dasar tebing.
Awalnya aku berpikir ibuku masih bisa selamat. Ternyata tidak, ibuku telah meninggal. Luka yang dideritanya terlalu serius. Paru-parunya bocor, tulang rusuknya hancur, dan kepalanya retak. Tidak ada lagi harapan untuknya selamat.
Aku harus hidup mandiri mulai saat itu. Aku memutuskan untuk melakukan kerja paruh waktu di sebuah swalayan untuk memenuhi biaya hidupku dan mencoba untuk melupakan segala kesedihan dengan banyak bekerja di luar. Akan tetapi, tetap saja rasa sedih akibat kematian ibuku itu belum juga terhapus. Aku jadi memiliki trauma besar dengan tebing. Aku takut melihat peralatan memanjat dan takut dengan ketinggian. Aku bahkan takut melihat gunung, mendengar suara debuman benda yang jatuh. Aku benar-benar selalu ketakutan.
Namun, suatu hari, aku teringat akan pesan ibuku, pesan terakhirnya. Aku tersadar bahwa selama ini aku telah terperangkap dalam kesedihan mendalam. Ditemani oleh Tian, sepupuku dekatku yang selalu menemaniku semenjak kematian ibuku, aku mulai bertekad untuk mengambil langkah besarku, keluar dari zona kesedihan mendalam itu.
Hingga suatu hari, tiba-tiba saja aku mendapatkan undangan lomba panjat tebing dari sebuah klub panjat tebing terbesar di kotaku. Tian berkata bahwa inilah saatnya untukku mengalahkan traumaku secara utuh.
“Ingat saja pesan ibumu. Jangan pernah tinggalkan panjat tebing, Mike.” Tian tersenyum padaku, memberi semangat.
Awalnya aku merasa bersemangat untuk mengikuti perlombaan tersebut. Namun, setelah sampai di lokasi, aku baru tersadar. Bodohnya, entah mengapa aku tidak menyadari sejak awal bahwa Mount Hill, tebing itu, adalah tebing dengan tinggi di atas tiga ribu kaki, yang dulu telah merenggut nyawa ibuku. Tebing itu bahkan masih terlihat sama dengan dulu. Bebatuan yang ada di sana masih sama. Pemandangannya juga masih sama. Hanya ada perbedaan pada alat perlengkapan keselamatan yang terlihat semakin banyak dan kuat.