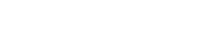Bronze

-ILUSTRASI AATLAS/PIXABAY -
Aku mengelus punggung ibuku dengan lembut, berusaha menenangkannya.
Lima tahun lalu, aku dan ibuku akhirnya kembali melakukan panjat tebing setelah sekian lama sibuk dengan urusan masing-masing. Kami kembali melakukan hobi kami sejak ayahku meninggal dunia akibat komplikasi beberapa bulan sebelumnya. Kami merasa benar-benar terpukul dan sedih. Karena itulah kami memutuskan untuk menjadikan panjat tebing sebagai tempat pelarian dari segala kesedihan itu. Selama memanjat tebing, pikiran kami kembali segar karena kami melihat banyak pemandangan menakjubkan dari atas ketinggian.
Ibuku memiliki mata yang benar-benar indah. Warna matanya bronze keemasan, yang selalu tampak berpendar indah tiap kali disinari cahaya matahari. Matanya yang dalam dan cantik itu membuatku seakan tengah memandangi matahari terbenam ketika melihat matanya, bronze cemerlang. Bahkan, aku sudah bisa menebak bahwa suatu saat nanti hal yang akan paling kurindukan dari ibuku adalah matanya.
“Apa yang membuatmu mencintai panjat tebing?” Ibuku bertanya dan tersenyum kecil. Wajah manisnya terlihat semakin cantik ketika ia mengembangkan senyum.
Aku menggeleng, “Entahlah, aku belum terlalu tahu.”
“Well, kamu memang masih baru di panjat tebing. Namun, ibu yakin, suatu saat nanti, kamu akan tahu mengapa kamu mencintai olahraga ini.” Ibuku tersenyum manis sambil menatapku.
Aku mengangguk semangat, lalu kembali fokus memandangi pegunungan yang terhampar di hadapanku dengan takzim. Dan, entahlah, mungkin saja Tuhan mengabulkan keinginkanku.
Semua pemandangan indah yang tersaji pada hari itu, semua hamparan gunung yang membentang pada hari itu, dan indahnya pemandangan kanopi-kanopi hutan yang terlihat hijau segar pada hari itu adalah pemandangan terakhir untuk seseorang.
Ya, pemandangan terakhir untuk ibuku.
Setelah selesai mengobrol, aku dan ibuku kembali melanjutkan perjalanan kami menaiki tebing. Awalnya kami sama-sama bahagia. Kami terus-menerus mengobrol tentang banyak hal, membicarakan hal apa pun yang terlintas, dan menikmati pemandangan menakjubkan yang tersaji di hadapan kami. Semuanya terasa biasa saja sampai ketika tiba-tiba saja ibuku mengatakan suatu hal yang membuatku keheranan,
“Jangan pernah berhenti untuk meraih impianmu, Mike. Apa pun impian itu. Beranilah untuk mengambil langkah besar. Beranilah untuk mendaki medan-medan yang terjal. Beranilah untuk menumpaskan semua kelemahanmu. Tidak peduli apa pun kondisimu, tidak peduli apa pun yang sedang terjadi. Teruslah kejar impianmu. Jangan pernah berhenti!” Ibuku melanjutkan dan menatapku dengan tatapan penuh arti. Mata bronze cemerlangnya terlihat berkilat mengesankan, berpendar indah, diterpa cahaya matahari yang menghangatkan. Entah mengapa, saat itu dia terlihat begitu cantik dan memesona.
“Kraakkkk!”
Tepat setelah ibuku berbicara, sebuah bunyi retakan panjang terdengar menggelegar dari dalam tebing yang tengah kami panjat. Semakin lama suara retakan itu terdengar semakin besar dan panjang, bahkan membuat tebing yang kami panjat bergetar hebat. Beberapa batuan kecil terlihat mulai luruh dari atas tebing, berdebum menghantam helm pelindung kepala kami, dan mengacaukan pandangan kami.
“Ibu!” Aku berteriak ketakutan dan menatap ibu sambil menangis histeris. Aku menempelkan tubuhku ke dinding tebing sambil gemetaran, takut tiba-tiba tebing tersebut roboh dan membuat kami tewas seketika karena jatuh dari ketinggian tiga ribu kaki. Pemandangan di sekitarku mulai terlihat buram. Pasir-pasir juga mulai berjatuhan menghantam kami, mengiringi luruhnya bebatuan. Sementara, di atas sana, tepat sepuluh meter di atas kami, sebuah bendera merah terlihat terpasang, tanda garis finish.
“Mike!” Ibuku menatapku dalam dan memegang pundakku dengan kuat.