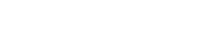Menulis Ulang Sejarah, untuk Apa?

ILUSTRASI Menulis ulang sejarah nasional Indonesia, untuk apa?-Foto Maulana Pamuji Gusti/Harian Disway -
Oleh: Probo D.A. & M. Aly A.B.*
MERESPONS artikel Dhimam Abror Djuraid yang berjudul History atau His Story? di rubrik Guest Editor di Harian Disway, Sabtu, 24 Mei 2025, wacana penulisan ulang sejarah nasional yang dipimpin Prof Susanto Zuhdi memang sudah sepatutnya diapresiasi.
Sebuah bangsa memang perlu merevisi ingatan kolektifnya secara berkala, bukan hanya untuk memperbaiki narasi yang timpang, melainkan juga untuk membentuk karakter moral dan mental masyarakatnya.
Namun, antusiasme itu tak boleh membuat kita luput dari pertanyaan mendasar: untuk apa sejarah ditulis ulang?
Berdasar pengalaman masa lalu, kita justru belajar bahwa sejarah kerap dijadikan alat legitimasi politik serta aparatus negara. Pun, glorifikasi berlebihan terhadap masa lalu masih mendominasi narasi sejarah nasional.
Melihat penulisan sejarah di arus utama, kita belum sampai pada titik menjadikan sejarah sebagai wadah yang dimiliki rakyat kecil, tetapi lebih sering jatuh pada cerita para tokoh besar serta kejayaan masa lalu kerajaan yang ada di antero Nusantara.
Sebagai contoh, Mohammad Yamin menggaungkan perjalanan gemilang Majapahit dengan menempatkan Gajah Mada sebagai figur sentral, bahkan menggambarkan wajah sang mahapatih yang konon mirip dirinya sendiri.
BACA JUGA:Desaku Maju Jadi Motor Penggerak Ekonomi Lampung
Harus diakui, pada awalnya sejarah yang ditulis pada masa itu berperan sebagai wacana pembentukan jati diri bangsa yang baru lahir. Maka, tak heran jika narasi sejarah pada masa itu cenderung berisi kejayaan imperium Nusantara masa lalu sehingga menciptakan bias di dalamnya.
Melanjutkan Mohammad Yamin, muncul Nugroho Notosusanto sebagai arsitek utama sejarah nasional Indonesia versi pertama. Ia diberi mandat oleh pemerintahan Orde Baru untuk merangkai narasi sejarah sebagai alat kekuasaan untuk memonopoli kebenaran, bahkan menjadi alat legitimasi kekerasan.
Penempatan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai kambing hitam tunggal atas Gerakan 30 September1965 (G-30-S) menjadi salah satu bukti bagaimana negara menempatkan sejarah sebagai aparatus untuk mengontrol wacana publik.
Narasi itu disebarkan melalui buku pelajaran, novel, dan film, lalu diam-diam mengendap menjadi kebenaran tunggal dalam ingatan kolektif bangsa, lalu menjelma sebagai kebenaran yang tak tergugat!
BACA JUGA: Empat Calon Berebut Posisi Direktur Polinela 2025–2029
Dampaknya, publik menempatkan PKI sebagai satu-satunya dalang dari peristiwa itu sehingga mempersekusi mereka tanpa pandang bulu. Dari situ, bisa dibilang bahwa sejarah pada masa Orde Baru ditempatkan sebagai alat politik dan legitimasi kekerasan.