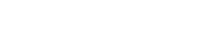Evaluasi Rapor Merah Jokowi untuk Perbaikan Pemerintahan Baru
Syaif Al Haq--
Gaya Presiden Jokowi juga dapat dilacak pada aspek lain selain kepemimpinan yang berdasar pada kekuatan populisme. Dalam hal ini, Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), memperkenalkan “Segitiga Kepemimpinan Jokowi”. Yaitu seperti pada bagan tiga segitiga (ambisi kekuasaan, kompetisi otoritarianisme, dan kekuatan populisme).
Dalam bagan tersebut dapat difahami bahwasanya Presiden Jokowi dalam melenggangkan kekuasaannya berdasar pada trias gaya kepemimpinan (triad of leadership styles), yaitu kekuatan populisme sebagai sebuah modal politik utama, budaya feodalisme sebagai instrumen politik struktural, dan cara machiavellianisme sebagai paradigma berpolitik.
BACA JUGA:Pendaftaran PPPK Kemenag 2024 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Jadwalnya
Dalam segitiga kepemimpinan ini, kekuatan populisme menjadi fokus utama yang menekankan hubungan langsung antara Jokowi dan rakyatnya. Melalui berbagai program kebijakan populis, Jokowi memperkuat basis dukungan dan mempertahankan popularitasnya di mata masyarakat. Sementara itu, feodalisme dapat dilihat dari prinsip-prinsip hirarki, loyalitas, dan patronase yang tercermin dari pendekatan kepemimpinan Jokowi, yang menggambarkan masih kuatnya pengaruh feodalisme dalam struktur politik Indonesia, bahkan pasca reformasi. Sementara itu, Machiavellianisme menunjukkan strategi politik yang lihai dan pragmatis yang digunakan Jokowi dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Pendekatan ini mencakup manuver-manuver politik yang cerdas untuk mengatasi tantangan politik dan menjaga stabilitas politiknya. Dengan menggabungkan ketiga elemen ini, Jokowi membangun fondasi kepemimpinan yang kompleks dan menarik. Namun, beberapa pengamat kemudian menghubungkannya dengan era pra-reformasi
Pada era Orde Baru, dengan landasan pembangunan ekonomi berbasis pertumbuhan, rezim ini memutuskan untuk memprioritaskan stabilitas dengan membangun eksekutif yang kuat. Akibatnya, tumbuh dan berkembanglah rezim-rezim represif yang oleh Hurbert Feith disebut sebagai Repressive Developmentalist Regime. Rezim represif ini ditandai dengan berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tersingkirnya partisipasi politik rakyat, terbatasnya kebebasan pers, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, bahkan pelanggaran HAM dan perampasan hak-hak rakyat semakin mengemuka.
Selain itu, dalam rangka mempertahankan hegemoni dan kekuasaannya, rezim Orde Baru juga menempuh beberapa cara: (1) membangun sistem kepartaian yang hegemonik; (2) fondasi kekuasaan Orde Baru ditopang oleh penyatuan Presiden Soeharto, Abri, Golkar, dan Birokrasi; (3) membangun konfigurasi otoriter melalui penciptaan pembenaran-pembenaran konstitusional sehingga terciptalah otoritarianisme yang berlandaskan pada aturan-aturan formal. Dengan demikian, bila dilakukan interkoneksi antara gaya kepemimpinan Presiden Jokowi dan gaya kepemimpinan era orde baru, dapat ditemukan fakta bahwa setidaknya terdapat kesesuaian gaya yaitu berupa Budaya Feodalisme dan Cara Machiavellianisme, dengan hanya menyisakan kekuatan populisme sebagai ciri khas Presiden Jokowi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan era Jokowi tidaklah lebih baik dibandingkan era orde baru, termasuk di dalamnya terkait kebijakan di bidang hukum dan pembangunan.
Rapor Merah Kebijakan Hukum dan Demokrasi Era Jokowi
Menjelang berakhirnya periode terakhir kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden ketujuh Republik Indonesia, menuai banyak kritik, catatan dan kajian datang untuk menguji sejauh mana penyelenggaraan Negara telah tunduk pada prinsip demokrasi, HAM, dan rule of law. Dalam konteks demokrasi, era kepemimpinan Jokowi dianggap menjadi faktor determinan terhadap mundurnya demokrasi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa laporan internasional, yaitu 2020 The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia 2019, dan 2021 Democracy Report. Ketiganya menunjukan bahwa kualitas demokrasi telah menunjukkan adanya kemunduran (declining) signifikan.
Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola demokrasi Indonesia yang semula adalah demokrasi elektoral menuju pada “demokrasi yang cacat”. Bahkan, salah satu laporan yakni EIU juga menyatakan bahwa angka tersebut merupakan yang terendah dari 14 tahun terakhir. Terbaru, kasus pemilu 2024 dianggap sebagai puncak gunung es, bahwa kemunduran demokrasi benar-benar terjadi pada masa pemerintahan Jokowi, terutama berkaitan dengan pergeseran paradigma negara yang dahulu pasca reformasi menunjukkan paradigma moral, kemudian kembali menuju paradigma kekuasaan.
Dalam kasus yang sama, kebijakan hukum era Jokowi juga mendapat perhatian terutama terkait pembiaran atas nilai etika dan moral dalam proses pencalonan calon pemilu 2024. Padahal, dalam teori yang jamak difahami dalam ilmu hukum, dinyatakan bahwa hukum sejatinya harus tunduk pada moral dan kepentingan sosial yang lebih besar. Selain kasus diatas, terdapat beberapa kasus hukum lain juga yang dapat ditemukan dan menunjukkan bahwasanya pada era Jokowi hukum hanya dijadikan alat justifikasi penguasa untuk mendapat legitimasi institusional, seperti pada kasus Rempang, UU Cipta Kerja, UU KPK dan lain sebagainya. Hal ini sejatinya sesuai dengan ciri-ciri suatu sistem hukum totaliter berlandaskan paradigma kekuasaan, yakni: (1) Sistem Hukum tergantung putusan penguasa, (2) Hukum hanya dipakai sebagai “kedok” tertentu, (3) Penerimaan sosial terhadap hukum berdasar kesadaran palsu, (4) Sanksi Hukum mengandung pengrusakan terhadap ikatan sosial, dan (5) Bertujuan legitimasi institusional.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, kebijakan hukum dan demokrasi era Presiden Jokowi sejatinya menggambarkan sebuah kemunduran bagi perjalanan bangsa, dengan ciri-ciri totaliter dan otoriter yang melekat pada masa pemerintahannya. Tak ayal, berdasar kepada analisis objektif menunjukkan bahwa kepemimpinan Jokowi sering disebut sebagai neo-Orba oleh beberapa pihak, termasuk di dalamnya para pengamat, peneliti dan para ahli. Oleh karena itu, bila dianalogikan sebagai sistem penilaian pendidikan, maka sepatutnya rezim Jokowi mendapatkan Nilai tidak lebih dari 2.3 dalam sistem Indek Penilaian Kumulatif (IPK) atau tergolong kedalam kategori rapor merah sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan pada pemerintahan selanjutnya. (*)