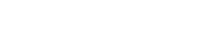Slamet, 28 Tahun Berjualan Kerupuk Bertahan dengan Cita Rasa dan Keuletan

Slamet saat menggoreng kerupuk usahanya. -Foto Sintia Maharani-
BANDARLAMPUNG – Di sebuah sudut kampung di Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, aroma gurih kerupuk yang baru diangkat dari wajan besar tercium kuat. Asap panas mengepul, menandai rutinitas yang tak pernah sepi di rumah produksi milik Slamet (57). Lelaki berperawakan sederhana itu sudah lebih dari dua dekade menggeluti dunia kerupuk –usaha yang kini memberinya omzet hingga enam juta rupiah per hari.
“Awalnya saya buka usaha di Jakarta, sekitar tahun 1997,” kenangnya sambil tersenyum.
“Dulu kerupuk mentahnya bikinan orang tua. Tapi lama-lama usaha di sana makin sepi. Akhirnya tahun 2012 saya pindah ke Lampung, bawa modal sekitar Rp200 juta buat buka produksi sendiri.” Sambungnya.
Langkah itu sempat membawa keberuntungan. Produksi kerupuk milik Slamet berjalan lancar, bahkan sempat mempekerjakan 12 orang karyawan.
Namun, badai usaha datang. Biaya operasional meningkat, cuaca tak menentu mengganggu proses penjemuran, dan modal makin menipis.
Pada 2022, ia memutuskan berhenti memproduksi sendiri dan beralih menjadi pengolah serta penjual kerupuk mentah dari berbagai distributor.
“Sekarang saya beli kerupuk mentah dari banyak tempat—ada yang dari Metro, Tanjung Bintang, Natar, sampai Palembang. Di sini cuma proses oven, goreng, dan packing,” ujarnya.
Di rumah produksinya, aktivitas berlangsung sejak pagi hingga malam. Sekitar sepuluh orang pekerja sibuk membungkus kerupuk panas ke dalam plastik bening.
Mereka bekerja dengan sistem borongan. “Satu ikat isi 10 bungkus, upahnya seribu rupiah,” jelas Slamet. “Jadi makin banyak bungkus, makin besar penghasilannya.”
Slamet sendiri masih turun langsung mengawasi proses oven dan penggorengan. Kerupuk mentah dioven selama empat jam, kecuali jenis rambak yang bisa mencapai lima belas jam.
Setelah itu, kerupuk digoreng dalam minyak panas—sekitar sepuluh jeriken berkapasitas 20 liter habis setiap hari. Untuk bahan bakar, ia masih setia menggunakan kayu bakar yang dibelinya satu juta rupiah per mobil dan cukup untuk sebulan.
“Dalam sehari bisa goreng sekitar satu setengah kuintal kerupuk mentah,” katanya. “Kalau sudah digoreng, hasilnya bisa sampai lima ratus ikat lebih.” Sambungnya.
Kerupuk-kerupuk itu dijual dengan harga sama rata, Rp32.000 per ikat. Di pasaran, harga kerupuk sejenis bisa mencapai Rp33.000 hingga Rp35.000, tapi Slamet memilih menjual lebih murah agar pembeli tak lari. “Yang penting lancar,” ujarnya mantap.
Kini, ia memiliki sekitar 20 pelanggan tetap yang tersebar di berbagai pasar—dari Karang Anyar, Way Kandis, hingga Kalianda.
Sebagian besar membayar tunai di tempat. Ada yang pedagang warung, ada juga penjual keliling yang rutin mengambil stok setiap beberapa hari.
Meski tak lagi memproduksi sendiri, usaha Slamet terus berputar. Dalam sehari, omzet kotornya bisa mencapai tiga hingga enam juta rupiah, tergantung banyaknya pesanan.
“Alhamdulillah, masih bisa jalan sampai sekarang. Yang penting kerja terus, jaga kualitas, dan nggak pakai bahan pengawet. Pembeli sekarang pintar, mereka tahu mana yang alami,” ujarnya menutup percakapan.
Di tengah derasnya arus industri makanan modern, Slamet dan kerupuknya menjadi bukti bahwa ketekunan dan kejujuran dalam berdagang tetap punya tempat di hati pembeli.
Gurih kerupuknya bukan hanya dari rasa, tapi juga dari cerita perjuangan panjang di balik setiap kepulan asap penggorengan.(mk-sintia/c1/nca)